
Universitas Diponegoro melalui Program Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya,
menyelenggarakan Diponegoro International Seminar on Interdisciplinary Linguistics pada Rabu,
20 Agustus 2025. Acara yang dipandu oleh Dr. Dwi Wulandari, M.A. sebagai moderator.
Rangkaian acara berlangsung dalam dua sesi, yakni Parallel Session pukul 09.15 WIB dan Panel
Session pukul 13.00 WIB. Melalui penyelenggaraan Diponegoro International Seminar on
Interdisciplinary Linguistics ini, diharapkan tercipta ruang dialog ilmiah yang produktif bagi para
akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk saling bertukar gagasan, memperluas wawasan, serta
membangun jejaring internasional di bidang linguistik. Selain memperkaya pemahaman tentang
isu-isu kontemporer bahasa dari berbagai perspektif, seminar ini juga diharapkan mampu
memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian linguistik yang lebih inklusif,
interdisipliner, dan relevan dengan tantangan global maupun kebutuhan lokal.

Narasumber panel yang pertama yakni Dr. Hunter Hatfield memaparkan materi berkaitan
dengan Deep Learning of Language Models and Linguistic Meaning. Hatfield menyampaikan
Large Language Models (LLMs) memiliki kemampuan untuk memproses bahasa, tetapi tidak
dapat sepenuhnya memahami maknanya seperti manusia. Makna dalam bahasa manusia berasal
dari berbagai sumber, termasuk simulasi pengalaman dengan tubuh, pengetahuan semantik
(hubungan antar item), dan pengetahuan episodik (pengalaman dan cerita pribadi). Sementara itu,
LLMs bekerja dengan memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat dan merekam “konteks”
dari kata-kata tersebut, yang dienkode sebagai vektor. Karena LLMs tidak memiliki tubuh, pikiran,
atau pengalaman, mereka tidak dapat memiliki pengetahuan episodik atau simulasi seperti manusia.
Oleh karena itu, mereka lebih baik dalam menjawab pertanyaan yang melibatkan pengetahuan
semantik umum daripada pertanyaan yang membutuhkan pemahaman episodik. Hasilnya,
meskipun LLMs dapat “berbicara” seperti manusia pada umumnya, mereka kurang baik dalam
meniru individu tertentu dan terkadang “berhalusinasi” karena konteks mereka sangat berbeda dari
manusia.

Selanjutnya, materi tentang The Makuva case: a Linguistic Detective yang disampaikan
oleh Aone van Engelenhoven, Ph.D. Materi ini membahas bahasa Makuva di Timor-Leste yang
kini hampir punah dengan hanya puluhan penutur tersisa. Bahasa ini dulunya dipakai oleh
beberapa klan di daerah Tutuala dan sekitarnya, tetapi berangsur-angsur ditinggalkan demi
Fataluku yang dianggap lebih bergengsi. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kerancuan
dalam klasifikasi Makuva karena ciri leksikalnya mirip Austronesia, sementara morfologi dan
sintaksisnya memperlihatkan pengaruh Papuan. Kini, Makuva tidak lagi berfungsi sebagai bahasa
komunikasi sehari-hari, melainkan dipertahankan secara tersembunyi sebagai bahasa ritual dan
identitas etnis, diajarkan hanya kepada perwakilan tertentu dari klan sebagai bagian dari tradisi
sakral.
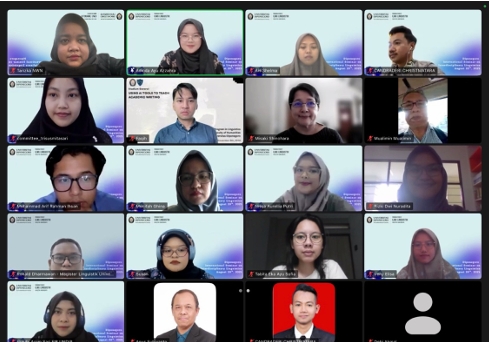
Pemateri selanjutnya yakni Ruanni Tupas, Ph.D. dengan materi Linguistic (in) justice and
Unequal Englishes. Materi ini membahas konsep ketidakadilan bahasa yang muncul ketika cara
berbicara atau variasi bahasa seseorang dianggap lebih rendah dibandingkan yang lain. Sejarah
“Global English” yang berakar dari kolonialisme melahirkan hierarki bahasa, di mana beberapa
ragam Inggris dianggap benar dan bergengsi, sementara yang lain dipandang salah atau tidak sah.
Fenomena seperti native speakerism, ideologi defisit bahasa, diskriminasi aksen (accentism), serta
praktik homogenisasi dan subtraktif dalam pendidikan memperkuat ketidaksetaraan ini,
berdampak pada marginalisasi penutur, rendah diri, dan penurunan prestasi akademik. Sebagai
alternatif, pendekatan yang menekankan keberagaman, keterhubungan lintas bahasa (translingual
dispositions), serta pengakuan kesetaraan semua bentuk bahasa Inggris diusulkan untuk melawan
ketidakadilan linguistik.
